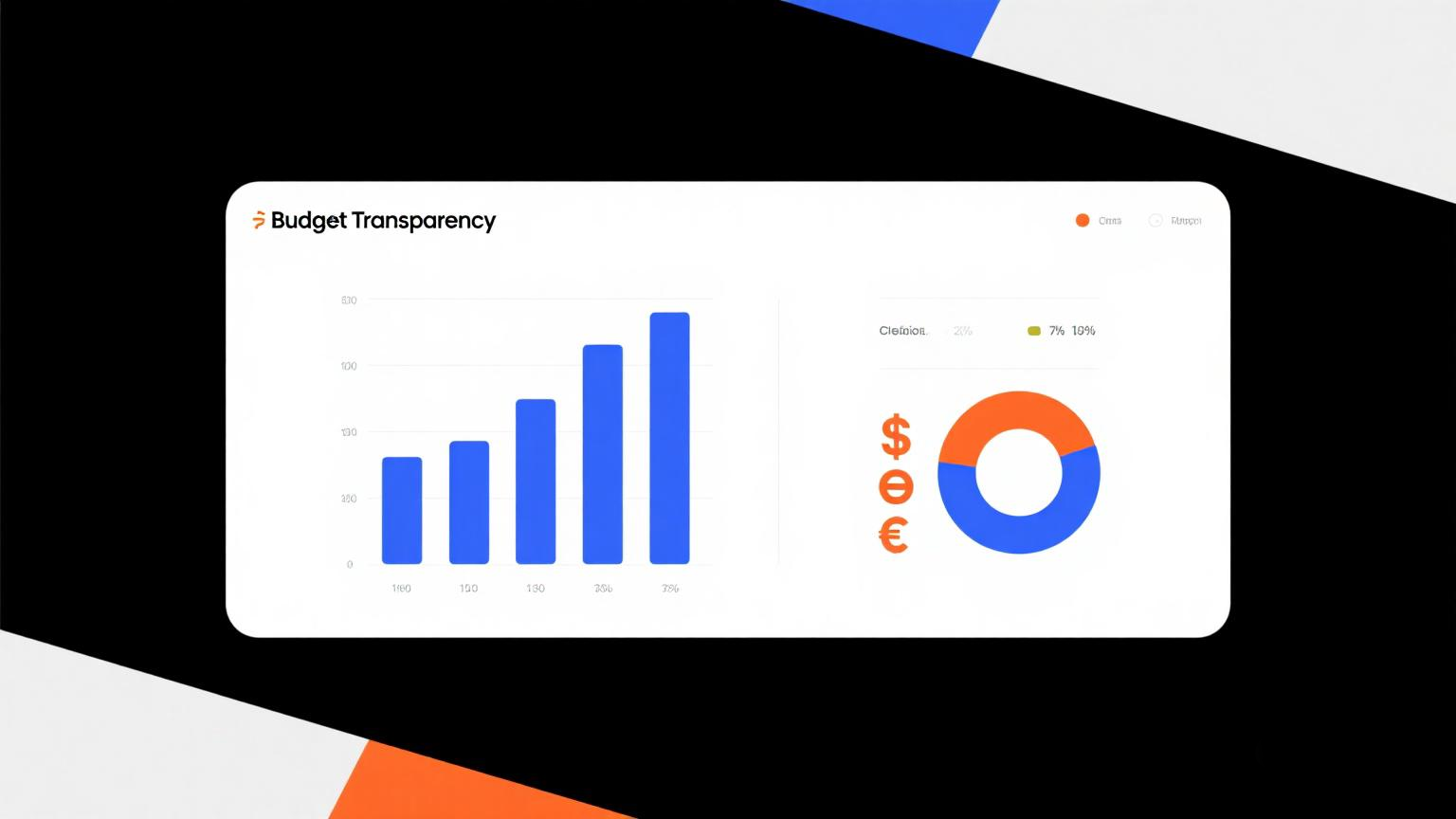Opini Pribadi
Oleh: Agus Agus Harianto
Bojonegoro – Transparansi anggaran di daerah ini kadang mirip menu di warung kopi.
Ada daftar harga yang ditempel di dinding untuk semua pelanggan, tapi ada juga “harga khusus” yang cuma tahu kalau sudah dekat sama pemilik warung.
Laporan anggaran memang ada, kertasnya putih, tulisannya rapi. Tapi siapa sangka, di balik meja ada kertas lain: hitam.
Isinya angka-angka yang tak pernah nongol di papan publik. Yang putih untuk rakyat, yang hitam untuk kalangan tertentu.
Lalu muncul pertanyaan tajam: kenapa kertas hitam harus ada? Apakah kertas putih tidak cukup? Kalau semua anggaran jelas, kenapa harus ditambah versi bayangan?
Ataukah kertas hitam memang disiapkan sebagai ruang abu-abu—tempat menitipkan kepentingan, menitipkan potongan, atau sekadar mengaburkan jejak?
Lebih jauh lagi, publik juga bertanya: kemana sisa anggaran di dalam kertas hitam itu dialirkan? Apakah kembali ke kas daerah, atau justru terselip ke kantong pihak-pihak yang berkepentingan?
Pertanyaan ini sering tidak pernah mendapat jawaban terang. Yang tersisa hanya gosip, bisik-bisik, dan tanda tanya besar.
Publik melihat ini bukan lagi transparansi, tapi koreografi. Seperti panggung sandiwara birokrasi: semua aktor tampil gagah, laporan disusun indah, lalu diakhiri tepuk tangan dari para pengawas.
BPK dan Inspektorat pun sering hanya jadi penonton VIP: duduk nyaman, melihat naskah pertunjukan, tanpa pernah benar-benar menelisik apa yang terjadi di balik panggung.
Masalahnya, uang yang dipakai bukan milik segelintir orang, tapi milik rakyat. Kalau anggaran jadi bahan sulap—muncul putih di papan, hilang hitam di meja—maka kepercayaan publik pun ikut terkikis.
Transparansi sejati tidak butuh kertas hitam. Ia hanya butuh satu hal: kejujuran.
Rakyat bukan menunggu tontonan, tapi kepastian bahwa setiap rupiah kembali untuk kepentingan bersama, bukan untuk dekorasi panggung kekuasaan.